
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
Banjir dan longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera pada penghujung 2025 kembali menyingkap paradoks klasik kebencanaan Indonesia, berupa alam yang rusak, negara yang tersendat di level kebijakan, tetapi tetap ditopang oleh kerja senyap para pelaksana di lapangan.
Padahal, Aceh dan Sumatera bukan wilayah asing bagi bencana hidrometeorologi. Namun kali ini, daya rusaknya melampaui ingatan kolektif masyarakat setempat.
Hujan ekstrem yang turun tanpa jeda selama berhari-hari memang menjadi pemicu langsung. Akan tetapi, faktor struktural yang memperparah dampak bencana jauh lebih dalam, yakni degradasi hutan sebagai penyangga ekosistem.
Alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan sawit skala besar, konsesi HPH, dan aktivitas pertambangan telah menggerus kemampuan alam menyerap dan menahan air.
Ketika hujan ekstrem datang, sungai tak lagi mampu menampung limpasan. Lumpur, batu, dan batang kayu berdiameter besar meluncur ke permukiman, menimbun rumah, jalan, dan fasilitas publik dalam hitungan jam.
Dalam situasi darurat seperti itu, publik berharap negara hadir cepat dan utuh. Namun yang kembali terjadi adalah keterlambatan informasi di tingkat pusat.
Presiden dinilai tidak segera memperoleh gambaran utuh mengenai skala bencana. Lebih problematis lagi, sejumlah pernyataan pejabat kementerian terkesan normatif dan tidak berbasis data lapangan, yaitu sebuah pola lama yang kerap muncul saat birokrasi terjebak pada laporan administratif, bukan realitas faktual.
Ketika pemerintah daerah terdampak secara terbuka menyatakan ketidakmampuan menangani bencana dengan sumber daya yang ada, tuntutan agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional pun mengemuka.
Status ini bukan semata simbol politik, melainkan instrumen hukum dan administratif untuk membuka akses anggaran, mempercepat mobilisasi lintas kementerian, serta memungkinkan solidaritas internasional berjalan tanpa hambatan psikologis dan prosedural.
Namun di tengah tarik-menarik politik kebijakan itu, kerja nyata justru berlangsung tanpa sorotan. Sejak Gubernur Aceh menetapkan status tanggap darurat, yang diperpanjang hingga 25 Desember 2025, BNPB, TNI, dan relawan lokal bekerja nyaris tanpa jeda.
Kodam Iskandar Muda mengerahkan sekitar 13 batalyon, terutama satuan zeni, untuk membuka akses wilayah yang terisolasi. Distribusi logistik, evakuasi korban, hingga pembangunan jembatan darurat (jembatan belly) dilakukan di tengah medan ekstrem dan cuaca yang belum sepenuhnya bersahabat.
Fakta lapangan menunjukkan betapa beratnya tantangan itu. Banyak titik bencana hanya bisa dijangkau melalui udara. Pengiriman logistik darat kerap terhenti oleh putusnya jembatan dan longsoran. Seorang relawan mencatat, pada fase awal bencana, pengiriman bantuan seberat tiga ton dari Banda Aceh ke Aceh Tengah membutuhkan biaya hingga Rp25 juta, dimana sebagian besar untuk menyeberangi sungai dan mengangkut barang secara manual. Angka ini bukan sekadar soal logistik, melainkan cermin mahalnya harga keterisolasian akibat rusaknya infrastruktur dan tata ruang.
Di tengah situasi tersebut, narasi publik justru kerap menyudutkan para pelaksana lapangan. Kritik diarahkan kepada BNPB, TNI, dan relawan, seolah-olah keterlambatan distribusi bantuan adalah akibat kelalaian mereka.
Padahal, pemantauan langsung menunjukkan sebaliknya: mereka bekerja “day to day”, menembus medan sulit dengan segala keterbatasan. Helikopter dan pesawat sayap tetap dikerahkan untuk dropping logistik, sementara ratusan truk berjuang di jalur darat yang rawan longsor.
Yang patut dikritisi secara lebih jujur justru absennya orkestrasi kebijakan di level pusat. Ketika status bencana nasional tidak ditetapkan, sebagian kementerian terkesan mengambil jarak, seolah tanggung jawab kemanusiaan berhenti pada batas formal kewenangan.
Sikap semacam ini bukan hanya mencederai rasa keadilan sosial, tetapi juga melemahkan semangat gotong royong nasional yang seharusnya menjadi fondasi penanganan bencana.
Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, tantangan akan jauh lebih kompleks. Pemulihan tidak bisa dijalankan secara sektoral dan sporadis.
Presiden Prabowo dihadapkan pada ujian konsistensi, apakah negara akan benar-benar hadir secara terpadu, atau kembali membiarkan BNPB dan TNI bekerja sendiri di garis depan. Rehabilitasi dan rekonstruksi menuntut perencanaan matang, berbasis data risiko, tata ruang berkelanjutan, serta keberanian meninjau ulang kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang selama ini memperbesar kerentanan bencana.
Sebuah ungkapan sinis namun reflektif kembali relevan, bahwa ketika bencana datang, orang mengingat Tuhan, BNPB, dan TNI; ketika keadaan normal, semuanya dilupakan.
Tantangan kita adalah memastikan negara tidak ikut menjadi bagian dari kelupaan itu. Sebab, bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan cermin dari pilihan-pilihan politik dan kebijakan yang kita ambil jauh sebelum hujan pertama jatuh.[]





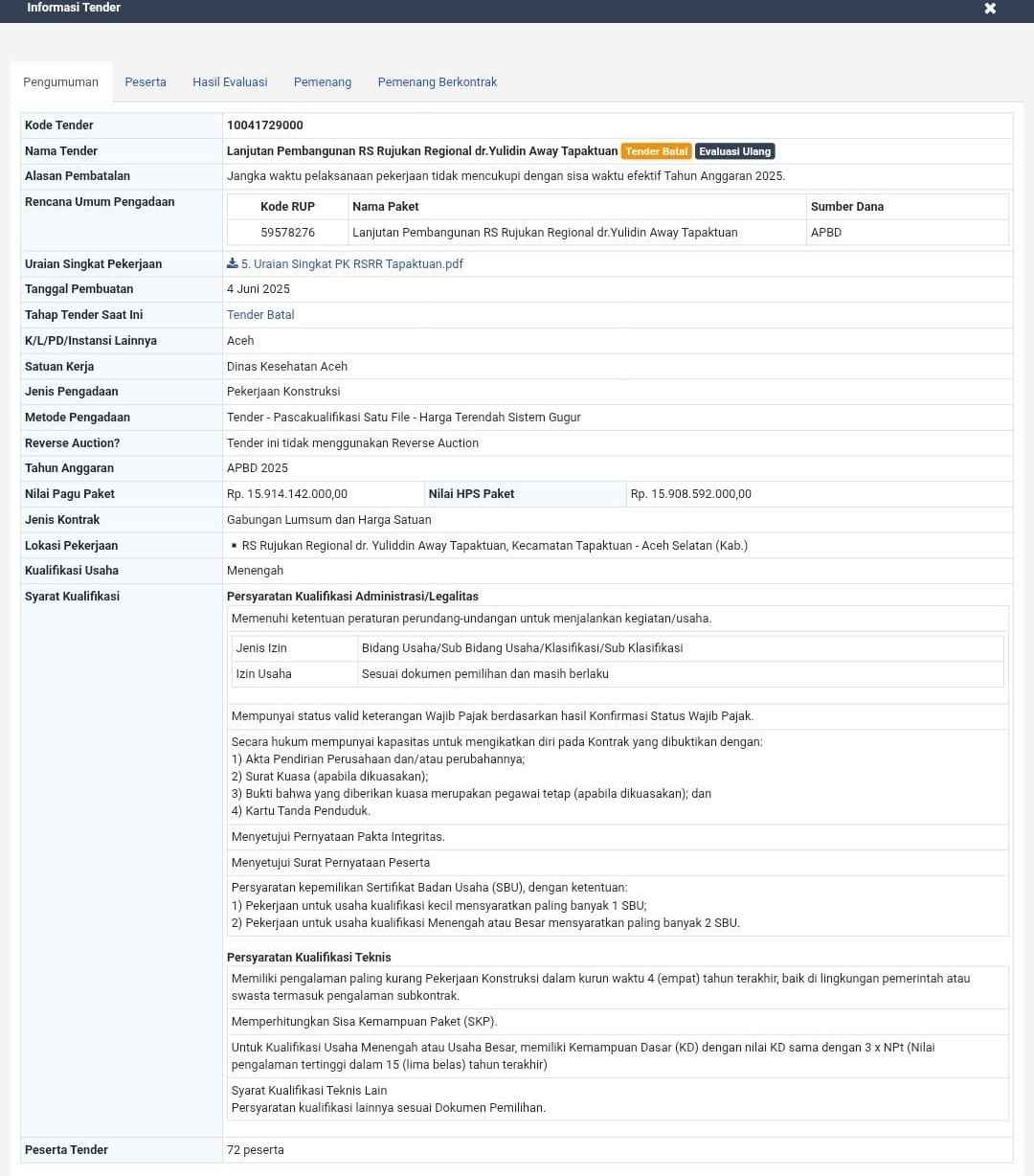








Tidak ada komentar