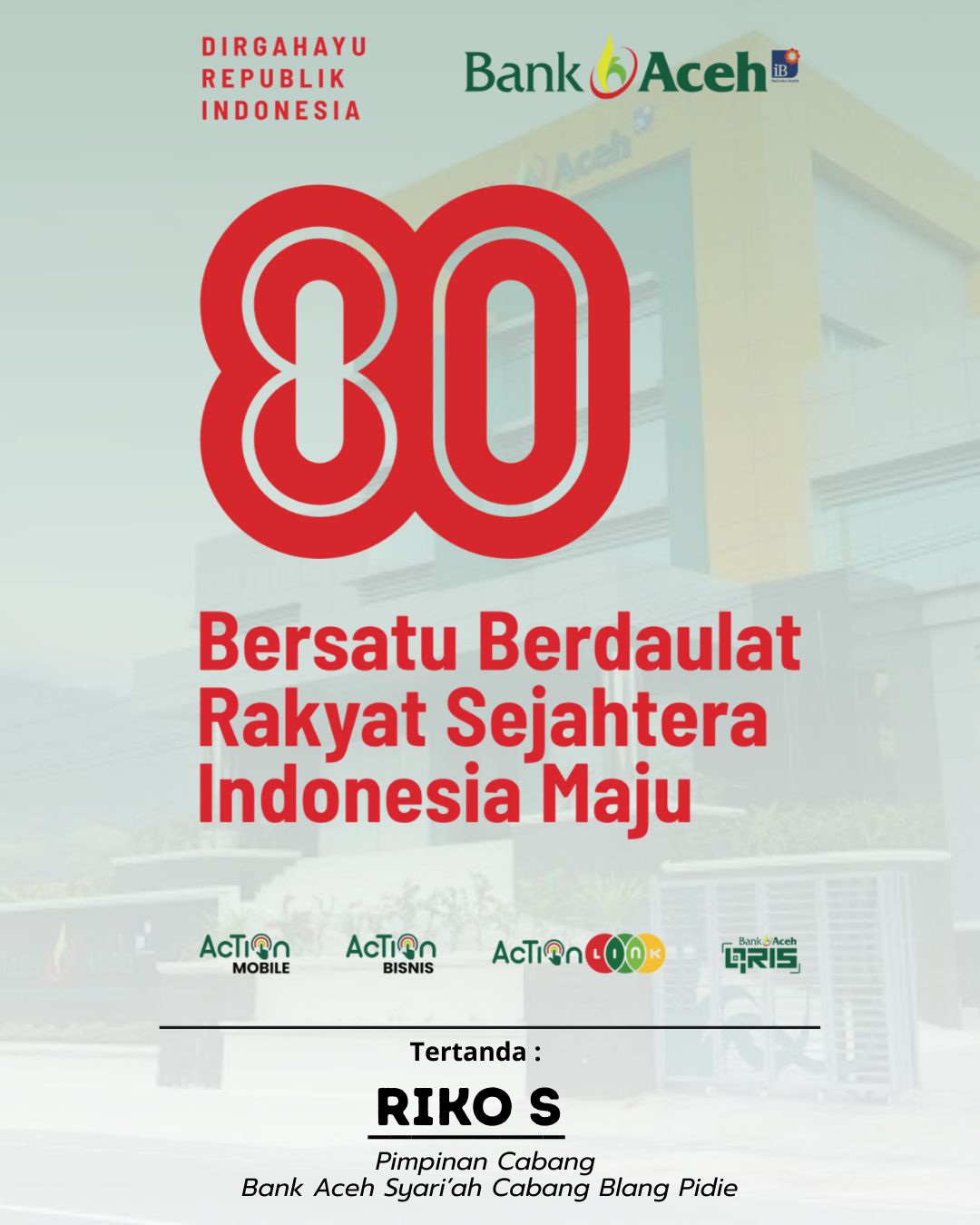Oleh : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 melahirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publik menaruh harapan besar bahwa lembaga ini akan menjadi benteng terakhir menjaga integritas sektor keuangan nasional.
OJK diberi mandat mengawasi perbankan agar tunduk pada aturan, disiplin pada prinsip kehati-hatian, serta melindungi hak-hak nasabah.
Namun, kasus dugaan praktik mafia perbankan di PT Bank UOB Indonesia memperlihatkan betapa taring OJK tumpul menghadapi bank asing yang diduga melanggar hukum di Indonesia.
Kasus yang kini bergulir di Mahkamah Agung melalui perkara Nomor 754/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst menunjukkan betapa seriusnya dugaan pelanggaran tersebut. Aset nasabah berupa SHGB No. 81 dengan luas tanah 17.220 m² dan bangunan 4.500 m², bernilai lebih dari Rp87,7 miliar, diduga digelapkan oleh pejabat tinggi bank. Gugatan ganti rugi senilai Rp100 miliar masih berproses di tingkat kasasi.
Ironisnya, di tengah proses hukum, manajemen PT Bank UOB Indonesia justru mengirimkan surat penagihan miliaran rupiah kepada nasabah, lengkap dengan rincian bunga Rp5,2 miliar, denda keterlambatan Rp2,3 miliar, dan total piutang Rp16,8 miliar.
Langkah ini bukan hanya melawan hukum, tetapi juga menegaskan adanya arogansi bank asing dalam memperlakukan hukum Indonesia. KUH Perdata, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta prinsip jurisprudensi jelas mengatur bahwa hak perdata nasabah tidak boleh dilanggar sebelum ada putusan hukum tetap.
Mengirimkan surat tagihan dan peringatan pelunasan hutang dalam tempo 7 hari sebelum putusan inkrah bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelecehan terhadap hukum nasional.
Kajian hukum perbankan, seperti yang diulas Zulkarnain Sitompul (2019) mengenai prudential banking principle, menegaskan bahwa pengawasan perbankan tidak semata administratif, tetapi juga moral: menjaga kepercayaan publik.
Jika bank asing dibiarkan melakukan praktik ilegal tanpa sanksi, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan akan tergerus.
Data OJK tahun 2024 memperlihatkan lebih dari 11.000 pengaduan masyarakat terkait sengketa perbankan, mayoritas menyangkut penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran perjanjian kredit.
Angka ini menegaskan bahwa masalah integritas perbankan di Indonesia bersifat sistemik, bukan insidental.
Sejarah juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan regulator selalu membuka ruang bagi skandal besar.
Jiwasraya dengan kerugian Rp16,8 triliun, Asabri dengan kerugian Rp22,7 triliun, hingga bailout Bank Century dengan kerugian Rp6,7 triliun, semuanya berakar dari pengabaian prinsip kehati-hatian dan lemahnya pengawasan.
Kasus UOB hanya menambah daftar panjang bukti bahwa pengawasan OJK kerap lebih sibuk membuat aturan di atas kertas, ketimbang menegakkan aturan di lapangan.
Pertanyaannya, apakah OJK benar-benar independen, atau justru terjebak dalam relasi kuasa dengan bank-bank besar? Jika lembaga pengawas tidak berani menindak, bagaimana publik bisa percaya pada sistem perbankan? Pada titik ini, krisis kepercayaan bukan hanya menimpa bank yang terlibat, tetapi juga mencoreng reputasi OJK sebagai otoritas keuangan.Kasus UOB harus menjadi titik balik.
OJK tidak boleh sekadar menjadi lembaga administratif yang sibuk dengan laporan dan sosialisasi, tetapi harus tampil sebagai penegak hukum yang melindungi hak-hak nasabah.
Tanpa itu, OJK hanya akan dikenang sebagai institusi mandul yang lahir dengan mandat besar, tetapi mati sebagai penonton di tengah maraknya mafia perbankan asing yang bebas bermain di Indonesia.[]