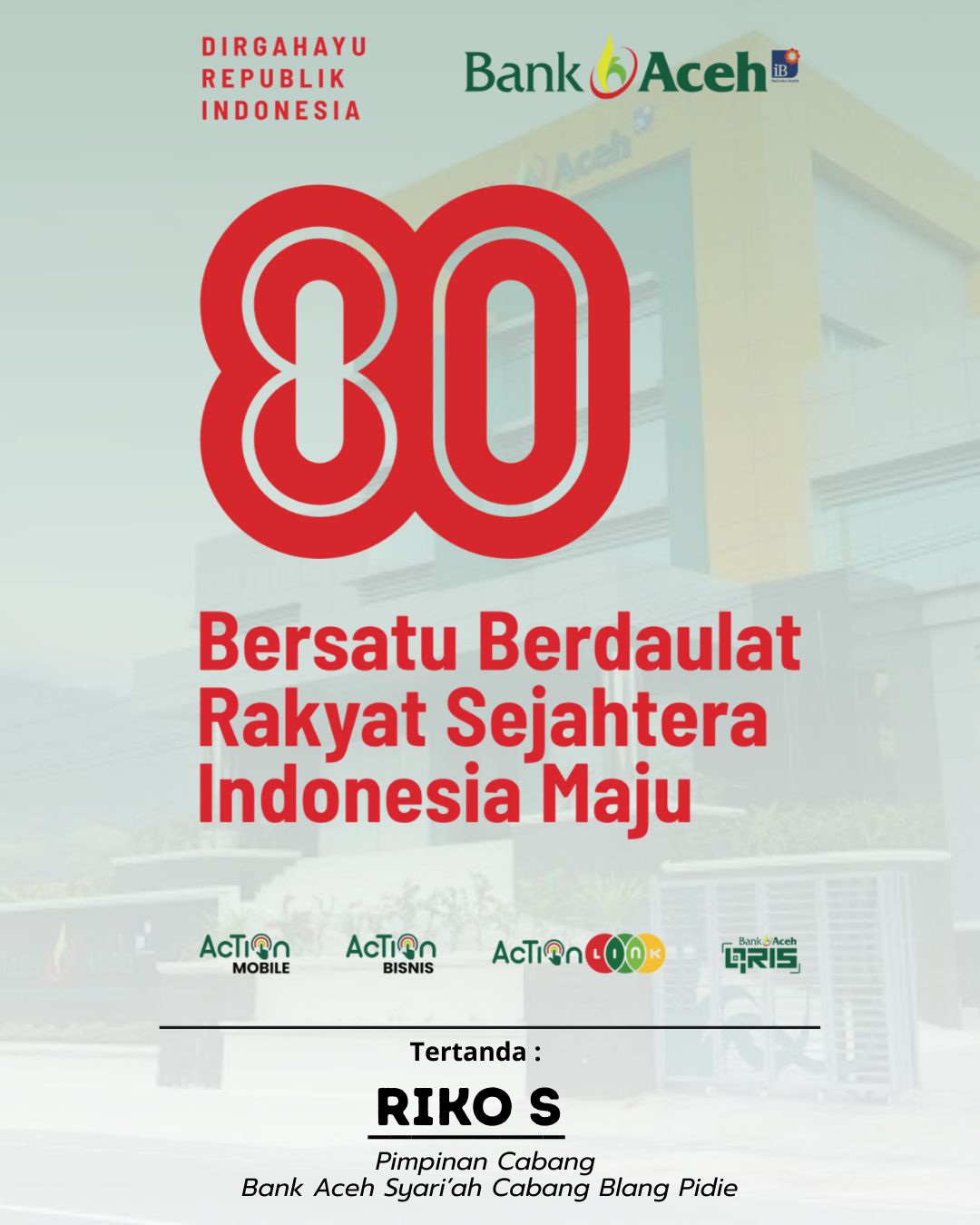PENDIDIKAN sejatinya adalah cermin masa depan bangsa. Namun, cermin itu kini tampak retak. Ia masih memantulkan bayangan, tetapi kabur dan terdistorsi.
Kita melihat anak-anak berseragam putih abu-abu menenteng gawai, guru sibuk mengisi aplikasi digital, dan pemerintah menggembar-gemborkan “merdeka belajar”.
Tapi di balik gegap gempita jargon itu, wajah pendidikan nasional memperlihatkan luka lama yang belum sembuh ketimpangan, komersialisasi, dan kehilangan arah moral.
Konsep Merdeka Belajar yang diperkenalkan pemerintah sejak 2019 di bawah kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim sejatinya mengandung semangat besar: membebaskan proses belajar dari belenggu birokrasi dan ujian nasional. Namun, di lapangan, kemerdekaan itu sering kali hanya berhenti di tataran wacana.
Banyak guru masih bingung menafsirkan maknanya. Alih-alih merdeka, mereka justru terpenjara oleh administrasi yang menumpuk dan penilaian berbasis platform digital yang menekan kreativitas. Sampai sekarang hal tersebut masih menjadi momok.
Sekolah masih identik dengan rutinitas: absen, tugas, ujian, laporan. Pembelajaran yang seharusnya berpusat pada siswa (student-centered learning) sering tergantikan oleh pola mengajar yang monoton.
Padahal, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.
Namun, bagaimana mungkin semua itu tercapai jika guru dibebani kerja administratif yang menyita waktu mendidik?
Di beberapa daerah, guru bahkan dituntut menguasai teknologi pembelajaran daring tanpa pelatihan yang memadai.
Ketika mereka gagal mengisi data di aplikasi Dapodik, mereka dicap tidak profesional. Sistem yang semestinya mempermudah justru menindih kebebasan pedagogis yang dijanjikan.Ujungnya siswa jadi korban oleh sistem ini, akibat gurunya disibukkan dengan hal administrasi.
Ujung Tombak yang Tumpul
Wajah pendidikan kita juga memantulkan ketimpangan yang mencolok antara kota dan desa. Di sekolah-sekolah unggulan di Jakarta, Bandung, atau Surabaya, pembelajaran sudah memakai smart classroom dan learning management system berbasis AI.
Namun di pelosok Sumatera, Kalimantan, atau Nusa Tenggara, masih banyak sekolah yang atapnya bocor, tanpa listrik, dan tanpa guru tetap.
Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan lebih dari 27 persen sekolah dasar di wilayah tertinggal belum memiliki akses internet memadai.
Sekitar 15 ribu sekolah masih kekurangan guru, sementara distribusi tenaga pendidik belum merata.
Di Papua misalnya, satu guru bisa mengajar enam mata pelajaran di tiga jenjang berbeda. Ketimpangan ini berimbas langsung pada capaian mutu pendidikan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2024 memang meningkat menjadi 74,4, tetapi kontribusi pendidikan di dalamnya masih timpang antarwilayah. Kota Yogyakarta mencatat rata-rata lama sekolah 11,3 tahun, sedangkan Kabupaten Nduga hanya 4,1 tahun.
Ini bukan sekadar angka, tetapi tanda betapa akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi privilese, bukan hak universal. Di sisi lain, dunia pendidikan tinggi menghadapi komersialisasi yang semakin mengkhawatirkan.
Beberapa universitas negeri menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga dua kali lipat, memicu gelombang protes mahasiswa di berbagai kampus. Padahal, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Jika hak itu berubah menjadi “kesempatan yang bisa dibeli”, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa telah tergadaikan. Guru adalah jantung pendidikan, tetapi mereka sering kali justru menjadi pihak yang paling terpinggirkan. Data Kemendikbudristek (2024) mencatat masih terdapat sekitar 600 ribu guru honorer yang menerima gaji di bawah upah minimum regional (UMR).
Sebagian besar dari mereka telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun tanpa kepastian status. Ironis, negara yang mengagungkan guru sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” ternyata memperlakukan mereka sebagai tenaga kerja temporer yang bisa diganti kapan saja.
Padahal, kualitas pendidikan tak mungkin meningkat tanpa penghargaan yang layak terhadap para pendidik. Lebih dari sekadar kesejahteraan, kini juga muncul krisis keteladanan.
Guru kehilangan ruang moral karena sistem pendidikan lebih menilai kinerja administratif ketimbang karakter. Banyak guru merasa tertekan oleh target kurikulum dan asesmen numerik, sehingga lupa membimbing nilai-nilai kebajikan.
Di sisi lain, kasus kekerasan di lingkungan sekolah meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sepanjang 2023 terdapat 2.536 laporan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Ini menunjukkan bahwa sekolah kita belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman dan beradab. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi, pendidikan kita perlahan kehilangan ruh kemanusiaannya.
Anak-anak sejak dini diajarkan coding, robotic, dan entrepreneurship, tetapi minim pelajaran empati dan budi pekerti. Mereka pandai berdiskusi, tetapi tidak terbiasa mendengar.
Mereka pintar berdebat, tetapi miskin kesadaran sosial. Padahal, Ki Hajar Dewantara telah lama menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan sekadar membuat manusia pandai, melainkan “menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.” Artinya, pendidikan tidak boleh berhenti pada kognisi, tetapi harus menyentuh sisi afeksi dan moralitas.
Sayangnya, orientasi pendidikan kini cenderung pragmatis. Sekolah diarahkan untuk mencetak tenaga kerja, bukan manusia beradab.
Nilai moral tergeser oleh nilai ekonomis. Ukuran keberhasilan pendidikan tidak lagi diukur dari kejujuran atau kepekaan sosial, tetapi dari skor ujian dan akreditasi. Maka lahirlah generasi yang cerdas secara digital, tetapi dangkal secara moral.
Regulasi Banyak, Implementasi Lemah
Pemerintah sebenarnya tidak kekurangan aturan. Ada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan, Permendikbudristek No. 50 Tahun 2022 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, hingga UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Semua regulasi itu menyebut prinsip yang mulia: pemerataan, mutu, dan keadilan. Namun, di tingkat implementasi, aturan-aturan tersebut sering kali mandek.
Misalnya, program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak yang seharusnya menjangkau daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), malah lebih banyak terserap di kota besar.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun kerap tersendat karena birokrasi dan ketidakjelasan pelaporan. Masalah utama bukan pada regulasinya, melainkan konsistensi pelaksanaan. Pendidikan kita terlalu sering menjadi proyek politik jangka pendek.
Setiap pergantian menteri, muncul istilah dan kurikulum baru. Padahal, pendidikan sejati membutuhkan kesinambungan kebijakan lintas rezim, bukan ego sektoral. Ketika pendidikan dijadikan komoditas, maka lahir kesenjangan baru antara “yang mampu” dan “yang tersisih.”
Padahal, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Sayangnya, porsi itu sering kali terserap bukan untuk peningkatan mutu guru atau sarana belajar, melainkan untuk proyek digitalisasi dan pengadaan alat yang tidak selalu relevan. Negara seharusnya memandang pendidikan sebagai investasi sosial.
Setiap rupiah yang ditanamkan pada pendidikan dasar dan menengah akan melahirkan pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas, dan ketahanan nasional.
UNESCO (2024) mencatat, setiap tambahan satu tahun masa sekolah rata-rata dapat meningkatkan pendapatan individu sebesar 10 persen di masa depan. Tetapi, manfaat itu hanya bisa dirasakan bila pendidikan diarahkan pada pemerataan, bukan elitisasi.
Menumbuhkan Pendidikan yang Berjiwa
Solusi dari semua persoalan ini bukan semata pada kurikulum baru, melainkan pada jiwa lama yang harus kita hidupkan kembali: pendidikan yang berbasis nurani. Negara perlu menata ulang arah kebijakan agar fokus pada pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar tenaga kerja global.
Pertama, pemerintah harus memperkuat literasi kemanusiaan. Pendidikan karakter, toleransi, dan kebangsaan di setiap jenjang.
Kedua, sistem kesejahteraan guru harus diperbaiki dengan meritokrasi yang adil. Guru tidak boleh lagi menjadi korban sistem kontrak berkepanjangan.
Ketiga, dana pendidikan harus dikelola secara transparan dan berpihak pada sekolah miskin di daerah tertinggal.
Keempat, perlu ada moratorium terhadap perubahan kurikulum dalam waktu dekat. Pendidikan butuh stabilitas kebijakan agar bisa beradaptasi secara natural.
Kelima, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat harus diperkuat, sebagaimana konsep Trisentra Pendidikan Ki Hajar Dewantara: keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai satu kesatuan.
Pendidikan tidak boleh diperlakukan sebagai urusan teknis atau proyek politik. Ia adalah urusan nurani, peradaban, dan masa depan bangsa.
Bila pendidikan dijalankan dengan hati yang jernih, maka setiap anak tak peduli lahir di kota atau desa, akan mendapat kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berprestasi.
Cermin pendidikan kita memang retak, tetapi belum hancur. Retakan itu bisa diperbaiki jika kita mau menatapnya dengan jujur: bahwa pendidikan hari ini belum adil, belum beradab, dan belum sepenuhnya membebaskan.
Namun, justru dari retakan itulah cahaya bisa masuk menerangi kesadaran bahwa bangsa ini harus membangun pendidikan dengan cinta, bukan sekadar kebijakan.
Sebab, pendidikan sejati bukanlah soal kurikulum atau teknologi, melainkan tentang bagaimana kita menumbuhkan manusia yang berpikir, berperasaan, dan berkeadaban.
Dan ketika itu terjadi, cermin pendidikan Indonesia akan kembali memantulkan wajah bangsa yang bermartabat.[]
Penulis : Desi Sommaliagustina (Dosen)
Sumber : Kompas.Com