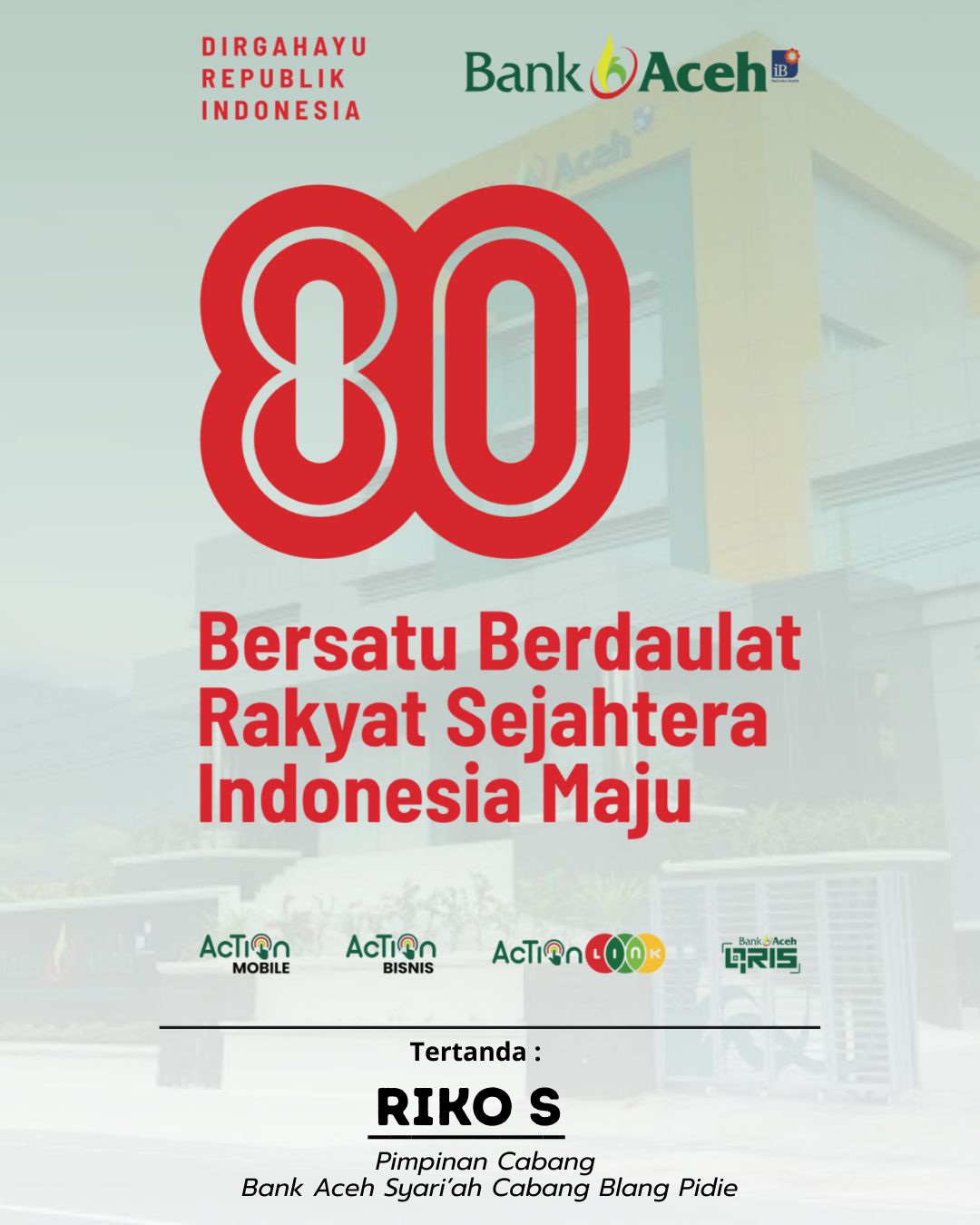DI TENGAH seretnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepala daerah tampaknya rela menjadikan jalan raya sebagai arena adu otot untuk mendongkrak kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Maka, jangan heran bila urusan pelat nomor berubah jadi adu gengsi antarprovinsi. Dan kejadian itu nyata di Pulau Sumatera.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution baru-baru ini menghentikan truk berpelat Aceh (BL) di jalan raya dan enteng meminta agar diganti pelat BK (plat kendaraan wilayah Sumut) seolah kendaraan Aceh melanggar hukum di tanah Sumut.
Gestur itu terekam video dan viral, lalu dibalas dari Banda Aceh dengan nada menantang, tapi tetap dibungkus kesantunan khas Aceh sekaligus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun tak tinggal diam dan berujar, “Dipeu bloe, kamo bloe. Tapi tanyoe ta wanti-wanti chit.
Menyoe ka di peubloe, ta bloe. Menyeu ka gatai ta garoe.” Sederhananya, “kalau mau rebut, kami pun akan rebut. Tapi harus kita ingatkan dulu. Kalau sudah dijual, kita beli. Kalau gatal ya kita garuk.”
Kalimat itu tidak hanya menyulut emosi politik, ia juga mereduksi upaya pembungkaman administratif menjadi ala tontonan jalanan.
Secara hukum, posisi kendaraan berpelat BL sah untuk melintas di seluruh wilayah Indonesia.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjamin keabsahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dari mana pun selama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) valid.
Indonesia tidak mengenal mekanisme paspor kendaraan antarprovinsi. Plat nomor bukan izin melintas, tetapi jadi penanda registrasi fiskal di provinsi tempat kendaraan terdaftar.
Artinya, truk BL dapat saja dengan bebas keluar masuk Sumatera Utara, Jakarta, bahkan Papua, tanpa harus menanggalkan identitasnya.
Logika ini fundamental dalam sistem hukum lalu lintas nasional. Karena itu, ketika seorang gubernur menghentikan kendaraan dan meminta pelat diganti, publik wajar mempertanyakan dasar kewenangannya.
Kewenangan razia kendaraan juga tidak berada di tangan kepala daerah. Kewenangan itu melekat pada institusi kepolisian melalui Satuan Lalu Lintas, dengan dukungan teknis Dinas Perhubungan dalam operasi gabungan.
Kepala daerah memang dapat mengeluarkan kebijakan fiskal atau regulasi daerah, tetapi tidak memiliki hak atributif untuk memberhentikan, memeriksa, apalagi menindak kendaraan di jalan raya.
Tindakan semacam itu, jika dilakukan, jatuh dalam kategori penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power.
Oleh sebab itu, pembelaan bahwa aksi Bobby hanyalah sosialisasi sebenarnya merupakan pengakuan implisit bahwa ia sesungguhnya menyadari keterbatasan kewenangannya.
Namun, di mata publik, visualisasi gubernur menghentikan kendaraan di jalan raya sudah cukup kuat untuk memicu tafsir bahwa BL dianggap ilegal di Sumatera Utara.
Inilah yang membuat insiden ‘aksi ala koboi’ di jalanan itu lebih besar daripada sekadar salah paham. Di balik itu terdapat logika fiskal yang ingin diperjuangkan.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak provinsi. Penerimaannya masuk ke kas provinsi tempat kendaraan terdaftar.
Jika perusahaan logistik beroperasi penuh di Sumatera Utara tetapi mendaftarkan kendaraannya di Aceh, maka PKB dan BBNKB tentu akan mengalir ke Aceh.
Sumatera Utara hanya menanggung kerusakan jalan akibat truk-truk berat tersebut tanpa memperoleh penerimaan pajaknya.
Dalam bahasa fiskal, kondisi ini adalah bentuk kebocoran antarwilayah. Manfaat mengalir ke satu daerah, beban ditanggung daerah lain.
Ibarat kata pemilik kendaraan plat B (Jakarta) yang tidak dimutasi dan berkeliaran di provinsi lain, bayar pajak di Jakarta tapi ‘merusak’ jalanan di mana-mana.
Tidak mengherankan jika Bobby mengangkat isu ini sebagai problem yang perlu diatasi.
Di sisi lain, Aceh dengan status otonomi khusus memiliki insentif untuk menarik sebanyak mungkin kendaraan berplat BL karena itu memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Maka, konflik kepentingan pun tidak terhindarkan. Meski logika fiskalnya dapat dipahami, logika politiknya tidak otomatis menjadi sah.
Mutasi registrasi kendaraan hanya bisa dilakukan melalui prosedur administratif di Samsat, yakni mencabut berkas dari daerah asal, membayar BBNKB, lalu menerbitkan STNK dan pelat baru di daerah tujuan.
Proses ini bersifat permanen, bukan gonta-ganti sementara. Dengan demikian, wacana bahwa kendaraan BL yang masuk Medan harus mengganti pelat BK adalah jelas keliru dan bertentangan dengan hukum lalu lintas nasional.
Yang benar, bila perusahaan memang berdomisili dan beroperasi secara substansial di Sumatera Utara, maka mereka seharusnya mendaftarkan kendaraan operasional dengan pelat BK.
Dalam kerangka resmi, persoalannya terletak pada domisili pajak, bukan pada aktivitas melintas.
Sayangnya, tindakan menghentikan kendaraan di jalan menciptakan ambiguitas besar, seolah setiap kendaraan BL yang melintas di Sumatera Utara sudah bersalah.
Dari perspektif politik, tindakan Bobby dapat dibaca sebagai teater jalan raya. Ia ingin menunjukkan kepada publik Sumatera Utara bahwa ia serius membela fiskal daerah.
Menghentikan truk BL secara langsung memberikan simbol kuat bahwa ia berpihak pada PAD Sumatera Utara.
Di era politik yang sarat pencitraan belasan tahun terakhir, gestur semacam ini lebih mudah dicerna publik ketimbang penjelasan teknis tentang pajak daerah atau rancangan peraturan gubernur.
Namun, risikonya juga besar. Di Aceh, insiden ini dibaca sebagai diskriminasi terhadap pelat BL, simbol identitas daerah yang dilindungi status otonomi khusus.
Narasi bahwa Aceh dilarang masuk Sumatera Utara cepat menyebar dan memicu resistensi emosional. Pada titik ini, isu fiskal yang teknis berubah menjadi persoalan kedaerahan yang politis.
Semestinya Gubernur Aceh menahan tensi ini agar tidak makin berkobar, bahkan membakar, bukan ikut menanggapi dengan bahasa tantangan yang justru memperkeras persepsi konflik.
Peran seorang kepala daerah bukan sekadar membalas gertakan dengan gertakan, melainkan menjaga agar ruang dialog tetap terbuka dan api kecil fiskal tidak menjalar menjadi bara politik identitas.
Paradoks yang muncul jelas. Masalah sebenarnya berada di ranah administrasi pajak, tetapi ditampilkan di ranah lalu lintas jalan raya.
Administrasi seharusnya diselesaikan dengan regulasi, koordinasi antarprovinsi, dan mekanisme mutasi resmi.
Namun di panggung politik, persoalan itu dijadikan tontonan dengan menghentikan kendaraan di jalan, menciptakan kesan seolah ada pelanggaran nyata yang sedang ditindak.
Padahal, secara hukum, tidak ada pelanggaran. Peristiwa ini akhirnya lebih menyerupai gestur populis yang berpotensi merusak kepercayaan antardaerah ketimbang menjadi solusi kebijakan.
Jika ditarik ke level desain kebijakan, masalah ini bukan sekadar riak lokal antara Aceh dan Sumatera Utara, melainkan cermin dari kelemahan mendasar sistem fiskal daerah di Indonesia.
Fragmentasi pajak antarprovinsi membuat setiap daerah sibuk mengamankan pundi-pundinya sendiri, bahkan jika itu berarti mengorbankan koordinasi nasional.
Negara seperti membiarkan provinsi-provinsi menjadi semacam “kantong feodal fiskal” yang berlomba menarik pajak tanpa peduli distribusi beban infrastruktur.
Selama tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibiarkan berbeda-beda, arbitrase fiskal akan terus terjadi.
Perusahaan hanya perlu memilih lokasi registrasi yang paling murah, sementara jalan rusak tetap ditanggung provinsi lain.
Di sinilah kegagalan desain nasional paling telanjang terlihat, negara hadir sebagai wasit yang diam di pinggir lapangan, sementara provinsi dibiarkan berebut penerimaan di tengah jalan raya.
Perusahaan memilih mendaftar di provinsi yang lebih menguntungkan meskipun operasinya terjadi di tempat lain.
Kondisi ini bukan hanya menimbulkan ketegangan antarwilayah, tetapi juga mengurangi efisiensi ekonomi nasional.
Biaya transaksi mutasi kendaraan menjadi beban tambahan, sementara distribusi penerimaan tidak mencerminkan distribusi beban infrastruktur.
Karena itu, solusi sejati tidak cukup berhenti pada imbauan untuk mengganti pelat. Jalan keluarnya menuntut rekayasa kelembagaan fiskal yang lebih canggih dan terukur.
Jalur pertama adalah skema berbagi penerimaan lintas provinsi atau revenue sharing. Amerika Serikat dan Kanada telah lama menerapkan International Fuel Tax Agreement (IFTA), yakni mekanisme di mana operator truk melaporkan total jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar.
Ini menjadi dasar distribusi penerimaan pajak bahan bakar ke yurisdiksi tempat kendaraan benar-benar beroperasi. Dengan cara ini, beban infrastruktur diseimbangkan dengan penerimaan pajak.
Indonesia dapat mengadopsi prinsip serupa dengan memanfaatkan data Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR), catatan jembatan timbang digital, teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta sistem Global Positioning System (GPS) pada armada niaga untuk menentukan porsi PKB yang dialokasikan ke provinsi lintasan utama. Pendekatan ini lebih rasional ketimbang mengandalkan identitas pelat, sebab kerusakan jalan terbukti mengikuti fourth power law, yaitu dampak keausan meningkat secara eksponensial ketika beban gandar bertambah sedikit saja. Jalur kedua adalah harmonisasi tarif PKB antarprovinsi.
Selama ini disparitas tarif mendorong arbitrase fiskal, di mana perusahaan memilih lokasi registrasi semata-mata demi beban pajak yang lebih rendah meskipun operasi bisnisnya berlangsung di provinsi lain.
Fragmentasi tarif ini memicu kebocoran penerimaan dan mendistorsi arus logistik nasional. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), tersedia instrumen opsen atau piggyback tax yang memungkinkan sinkronisasi pengenaan PKB dan BBNKB.
Harmonisasi dapat dilakukan dengan mempersempit rentang tarif dan menstandarkan basis pengenaan, sehingga insentif untuk mendaftarkan kendaraan di provinsi lain berkurang.
Uni Eropa melalui skema Eurovignette memberi contoh bagaimana biaya penggunaan jalan bagi kendaraan berat ditentukan secara seragam berdasarkan jarak, tonase, dan standar emisi.
Dengan model itu, tidak terjadi migrasi registrasi lintas negara anggota hanya demi beban fiskal yang lebih rendah.
Jalur ketiga adalah memperkuat kerangka hukum diskresi agar pejabat daerah tidak mengulangi kesalahan menggunakan simbol politik di luar batas kewenangan formal.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menegaskan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan jika ada atribusi, delegasi, atau mandat yang sah, serta harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Dengan prinsip ini, gubernur memang berhak menggagas kebijakan fiskal, tetapi tidak sah jika mengalihkannya ke ranah penegakan hukum lalu lintas.
Proses yang benar adalah melalui regulasi daerah yang jelas, koordinasi antardaerah, masa transisi yang transparan, serta mekanisme mutasi kendaraan yang memberi kepastian hukum.
Tanpa itu, kebijakan fiskal akan selalu rawan dipelintir menjadi panggung populisme yang mengorbankan kepastian usaha dan stabilitas hubungan antarwilayah.
Dengan tiga jalur kebijakan tersebut, persoalan fiskal antara Sumatera Utara dan Aceh dapat didekati dengan cara yang lebih bijaksana karena rasional dan adil.
Revenue sharing memastikan beban infrastruktur sebanding dengan penerimaan pajak, harmonisasi tarif menutup peluang arbitrase fiskal, dan penguatan kerangka diskresi menjamin bahwa eksekusi kebijakan berjalan melalui mekanisme konstitusional, terukur, serta dapat diaudit publik.
Reformasi fiskal daerah berbasis data dan hukum inilah yang mampu mencegah konflik identitas sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional yang sehat dan berkeadilan.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai benarkah tindakan Bobby harus dijawab dengan analisis berlapis. Secara hukum, tindakannya menghentikan kendaraan BL di jalan raya tidak benar karena tidak memiliki kewenangan.
Secara fiskal, logikanya dapat dipahami karena Sumatera Utara memang dirugikan. Secara politik, tindakannya efektif sebagai panggung citra, tetapi berbahaya sebagai sebuah preseden.
Ia membuka ruang konflik antardaerah yang lebih besar daripada manfaat fiskal yang mungkin diperoleh.
Manalah bisa jalan raya dijadikan teater politik seakan menggantikan desain kebijakan yang harusnya disusun dengan penuh perhitungan.
Jika tujuan utamanya adalah keadilan fiskal, maka solusinya berada di meja perumus kebijakan, bukan di tengah jalan dengan menghentikan truk dan menuding pelat sebagai biang kerok.
Bobby, Bobby, entah logika apa pula yang sedang Anda pakai?.[]
Penulis : Jannus TH Siaahan (Doktor Sosiologi)
Sumber : Kompas.Com