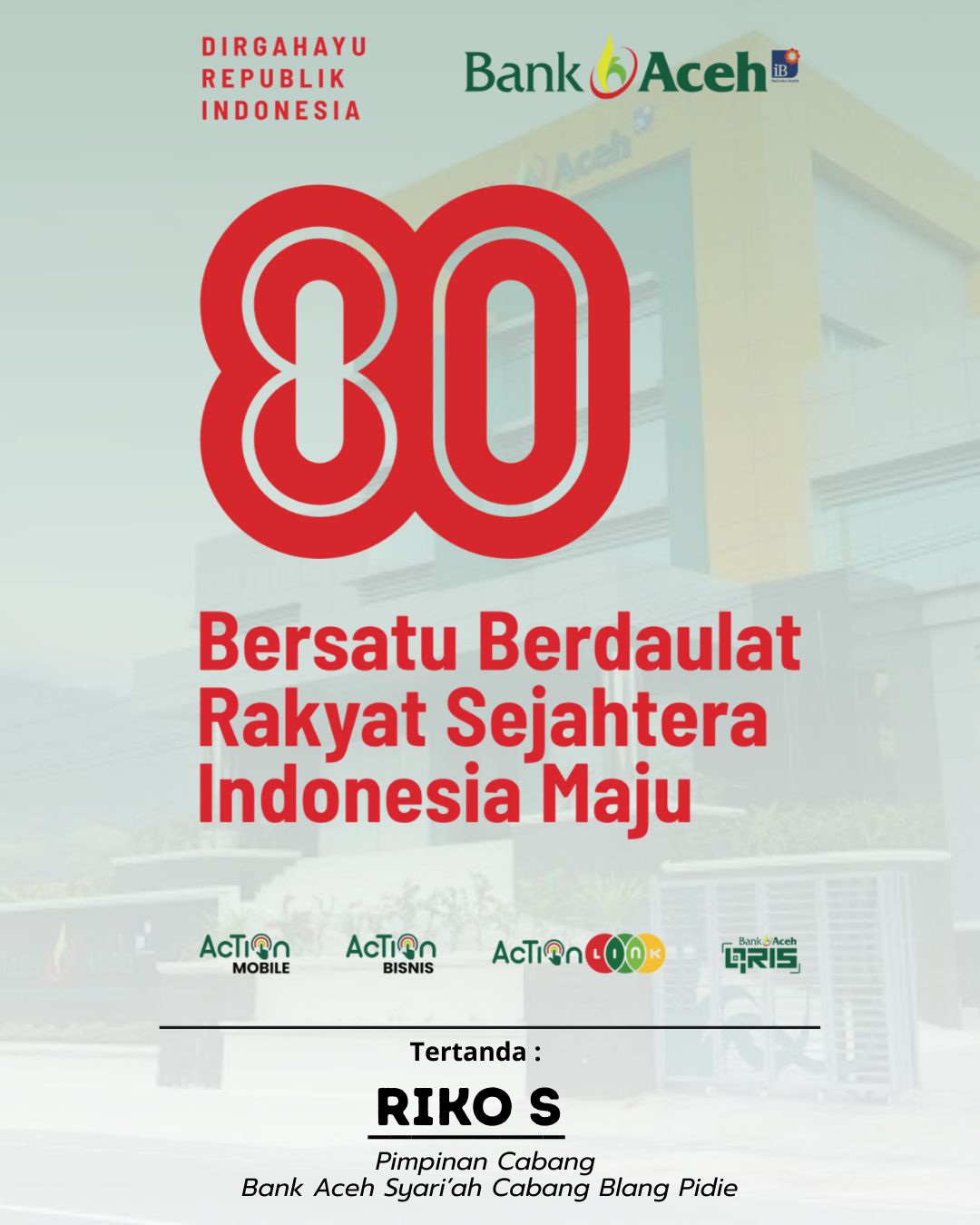GELOMBANG kerusuhan di Nepal pada September 2025 ini, mempresentasikan krisis sistemik akibat kegagalan transisi demokrasi pasca-monarki.
Ia bukan sekadar respons terhadap pemblokiran media sosial, tetapi manifestasi akumulasi kekecewaan atas tiga kegagalan struktural: institusi politik korup, disparitas ekonomi yang melebar, dan penyempitan ruang deliberasi publik. Bagi elite politik, pelarangan platform digital mungkin dilihat sebagai langkah stabilisasi.
Namun bagi generasi muda, yang kebanyakan Gen-Z, kebijakan memblokir media sosial merupakan simbol paling nyata dan terakhir dari negara yang lebih memilih represi ketimbang dialog; lebih memilih membungkam dan bukan mendengarkan.
Kebijakan pembatasan akses digital terbukti menjadi strategic miscalculation. Bagi populasi muda Nepal yang mengandalkan platform digital sebagai ruang ekonomi, sosial, dan politik, langkah ini tidak hanya memutuskan mata pencaharian, tetapi juga menghancurkan saluran aspirasi politik yang tersisa.
Situasi itu diperparah dengan viralnya fenomena “nepo kids” yang mengekspos hipokrisi elite penguasa; semakin memperjelas jurang pemisah antara elite politik dan warga biasa.
Konfluensi kedua faktor inilah yang mentransformasi ketidakpuasan menjadi gerakan sosial vertikal atau kemarahan terpendam menjadi mobilisasi massa berskala nasional.
Tiga dekade pasca-restorasi demokrasi, Nepal gagal memenuhi janji reformasinya. Data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran pemuda masih tinggi (sekitar 28 persen), mobilitas sosial tersumbat, sementara korupsi struktural telah menggerogoti jantung birokrasi sehingga menghambat distribusi sumber daya.
Bagi generasi muda Nepal, sistem politik yang ada tidak lagi dipandang sebagai solusi, melainkan bagian dari masalah. Mereka menyaksikan oligarki politik mengonsolidasi kekuasaan melalui jaringan patronase, sementara mayoritas populasi terjebak dalam ekonomi subsisten.
Wajar jika protes kali ini mengambil karakter pemberontakan generasi— deklarasi bahwa batas kesabaran mereka telah terlampaui.
Respons negara
Alih-alih meredakan ketegangan, pemerintah memilih jalur represif, bukan dialog. Aparat keamanan dikerahkan, tembakan dilepaskan, dan kantor-kantor pemerintah dibentengi bak menghadapi invasi asing. Puluhan nyawa melayang, ratusan lainnya terluka.
Kekerasan negara justru memberikan legitimasi moral tambahan bagi gerakan protes. Narasi publik dengan cepat bergeser dari penolakan terhadap kebijakan digital menjadi perlawanan terhadap state violence.
Krisis politik meruntuhkan sisa-sisa kepercayaan publik, memaksa perdana menteri dan presiden mengundurkan diri dan meninggalkan kekosongan kekuasaan. Dampak krisis melampaui ranah politik.
Sektor pariwisata—penyumbang 8 persen PDB—kolaps dalam seminggu. Investor asing menarik portofolio mereka. Pasar modal mengalami penurunan terburuk dalam sejarah.
Lebih parah lagi, terjadi erosi legitimasi institusi negara. Demokrasi, yang pernah dirayakan sebagai prestasi pasca-monarki, berada di ambang delegitimasi total.
Korban paling langsung adalah para pemuda—mereka yang turun ke jalan dengan keyakinan bahwa cita-cita demokrasi masih dapat diperjuangkan.
Namun, dampaknya juga menjalar kepada warga sipil yang terjebak dalam kekacauan, usaha lokal yang hancur, dan reputasi internasional Nepal yang porak-poranda di mata investor dan pelaku pariwisata.
Nepal perlu menghindari jebakan spiral kekerasan dan ketidakpercayaan. Beberapa langkah krusial berikut mungkin perlu segera diimplementasikan. Pertama, pemerintah transisi harus mengumumkan moratorium terhadap penggunaan kekuatan mematikan dan mengizinkan penyelidikan independen yang komprehensif untuk setiap insiden penembakan.
Akuntabilitas adalah prasyarat mutlak untuk pemulihan. Kedua, mengembalikan akses digital. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan langkah berani untuk membuka dialog dengan generasi muda.
Regulasi dunia maya perlu dirumuskan melalui forum inklusif yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan generasi muda.
Ketiga, mengambil respons ekonomi yang konkret. Protes ini pada hakikatnya adalah tentang adanya kekhawatiran akan masa depan yang suram.
Nepal memerlukan program padat karya, insentif kewirausahaan pemuda, dan reformasi pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pasar.
Menciptakan lapangan kerja adalah strategi de-eskalasi yang paling efektif. Keempat, melakukan reformasi anti-korupsi yang terukur.
Audit publik terhadap kekayaan pejabat, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta perlindungan bagi whistleblower harus menjadi prioritas.
Reformasi yang terlihat dan terukur dapat secara gradual memulihkan kepercayaan publik.
Kelima, perlu dialog nasional yang inklusif. Krisis ini hanya dapat diselesaikan melalui forum dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan: partai politik, organisasi masyarakat sipil, perwakilan agama, dan yang terpenting, suara generasi muda.
Dialog semacam ini bukanlah retorika, melainkan landasan baru bagi legitimasi politik. Baik pula jika komunitas internasional bersikap aktif.
Tekanan diplomatik untuk mendorong akuntabilitas, bantuan teknis untuk reformasi tata kelola, serta bantuan kemanusiaan bagi korban adalah hal yang mendesak.
Namun, intervensi harus dilakukan dengan hati-hati—memperkuat kapasitas domestik tanpa merusak kedaulatan dan keterwakilan rakyatnya.
Krisis Nepal adalah cermin dari benturan zeitgeist (semangat zaman): generasi baru yang menuntut inklusivitas melawan struktur kekuatan lama yang tertutup.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Nepal dapat kembali kepada “normalitas”, tetapi normalitas seperti apa yang ingin dibangun kembali—apakah kembali kepada status quo yang rapuh, ataukah beralih menuju konsensus demokratis baru yang lebih akuntabel dan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Jika para pemimpin dan masyarakat Nepal memiliki keberanian untuk memilih opsi kedua, maka krisis September 2025, berpotensi menjadi katalis untuk merekonfigurasi kontrak sosial antara negara dan warganya.
Namun, jika momentum ini disia-siakan, sejarah mungkin akan mencatat peristiwa ini sebagai awal dari kemunduran demokrasi yang panjang di atap dunia.[]
Pascal S Bin Saju (Wartawan Harian Kompas (Kompas.id) sejak Maret 1993 sampai 31 Desember 2022)
Sumber : Kompas.Com