
DI UMUR 80 Tahun, seharusnya negara kita telah menapaki tahap kedewasaan. Telah memiliki institusi mapan, demokrasi stabil, ekonomi yang adil, dan masyarakat tercerahkan.
Di usia yang mendekati satu abad ini kita masih berada dalam paradoks. Tampak dewasa secara umur, tetapi ringkih secara kualitas. Fenomena ini bukan anomali, tapi gejala kronis dari demokrasi prosedural yang belum tumbuh menjadi demokrasi substansial.
Elite politik dan ekonomi menguasai jalur kebijakan, mengendalikan narasi publik, dan memonopoli peluang kesejahteraan. Institusi hukum, yang seharusnya menjadi wasit netral, kerap berubah menjadi instrumen politik dan kekuasaan.

Elite politik memonopoli definisi kebenaran publik. Kebijakan publik kadang (malah sering) lahir bukan dari pertimbangan rasional atas kebutuhan rakyat banyak, melainkan dari lobi-lobi transaksional.
Model pembangunan ekonomi kita masih oligarki ekstraktif, yaitu distribusi kekayaan negara hanya berpindah dari satu lingkaran oligarki ke lingkaran lainnya. Sementara itu, bagi rakyat kebanyakan, pembangunan hanya menjadi berita baik yang tak pernah mampir di dapur mereka.
Bersuara dan berkarya
Negeri ini milik kita semua. Air, tanah, udara, dan masa depan bangsa ini bukan hak istimewa segelintir orang, bukan pula warisan dinasti, melainkan amanah berjuta rakyat dari Sabang sampai Merauke.
Dari Miangas hingga Pulau Rote. Setiap warga negara punya hak untuk bersuara, menyampaikan keresahan, menagih keadilan, dan merumuskan harapan. Suara rakyat adalah jiwa. Ia adalah tanda bahwa negara masih bernyawa.
Tapi suara yang terus-menerus disampaikan tanpa pernah ditanggapi hanya kebisingan yang sia-sia. Memang suara rakyat tak selalu enak didengar. Mereka bersuara karena cinta, bukan karena benci.
Malah yang berbahaya bukan ketika rakyat bersuara, tapi ketika mereka diam karena sudah kehilangan harapan. Kita juga harus jujur. Dalam atmosfer keterbukaan hari ini, bersuara menjadi jauh lebih mudah daripada berbuat.
Kita menulis status, membuat petisi, membuat podcast, membuat video kritik. Seolah semua masalah akan tuntas dengan status di medsos. Tentu membuat status bukan “dosa bernegara”.
Namun, ketika status menggantikan sikap, caption menggantikan komitmen, dan foto menggantikan fakta, maka kita sudah jauh tersesat. Perlu disadari bahwa bersuara saja tidak cukup.
Negeri ini tidak butuh hanya gema dan gaung, tapi juga telinga yang mau mendengar dan tangan yang mau berbuat. Ketika semua bersuara, sementara tak ada yang menyimak dan bergerak, maka kita hanya sedang membangun negeri dari gema, bukan dari tindakan.
Negeri ini butuh tangan-tangan yang turun ke lapangan, mengelola kebijakan dengan ulet, perlahan membersihkan birokrasi, dan membangun keadilan.
Tanpa itu, kita terjebak dalam negeri yang sibuk berbicara, tapi lumpuh dalam karya. Atau, hanya menjadi republik opini, bukan republik aksi.
Jika semua bersuara, tapi tak ada yang bertindak, maka negeri ini tak ubah sebagai negeri doa: penuh harap, penuh ratap, tapi tanpa langkah nyata yang mewujudkan cita. Semuanya berseru “aamiin”, tapi tak satu pun bergerak mewujudkan “aamiin” itu dalam bentuk kebijakan, kerja, dan keteguhan sikap. Negeri ini ramai dengan suara. Semua bicara. Semua mengeluh.
Semua mengkritik. Semua merasa paling tahu jalan keluar. Namun, ketika panggilan untuk bertindak datang, semua menoleh ke belakang, menunjuk orang lain, “Itu tugas mereka.” Negeri ini butuh keseimbangan.
Demokrasi bukan hanya tentang siapa paling lantang, tapi juga siapa paling berjuang. Negara yang sehat bukan yang hanya penuh debat, tapi juga penuh giat. Kita jangan terlalu mengandalkan perubahan akan datang dari Istana, dari parlemen, dari para elite politik, dan dari para tokoh besar.
Kekuatan perubahan ada di lorong-lorong pasar, di ruang kelas, di desa-desa, di komunitas kecil, di ruang-ruang sunyi tempat orang-orang bekerja jujur, meski tak disorot kamera. Kita harus mulai dari “lorong-lorong itu”.
Dari keluarga yang mengajarkan anaknya untuk tidak menyuap guru. Dari kepala sekolah yang menolak “proyek titipan”. Dari petugas desa yang menyalurkan bantuan tanpa menyunat.
Dari pemimpin muda yang memperlakukan rakyat sebagai warga negara bukan sebagai followers. Negeri ini milik kita semua. Maka semua harus bersuara. Setelah bersuara, kita harus bergerak. Bukan hanya menuntut keadilan, tapi juga menciptakannya. Jika hanya berbicara tapi tidak bekerja, kita hanya akan membangun negeri dari keluhan, bukan dari kerja dan karya.
Kita akan menjadi bangsa yang gemar membicarakan masalah, tapi tak pernah menyentuh dan menyelesaikanya. Maka, di tengah segala kegaduhan antara suara-suara yang menggema dan janji-janji yang bertebaran, kita mesti menjadi bagian dari solusi.
Karena negeri ini milik kita semua, hanya bisa diselamatkan jika semua mau berkarya. Indonesia akan terus hidup, bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju bukan karena warganya hanya “ngomel”, tapi juga cerdas dan cekatan.
Bukan hal salah kita berbeda pendapat. Kita bukan kru kapal Going Merry berbendera One Pice yang disatukan oleh logika bajak laut. Kita disatukan oleh kepercayaan, cita-cita, dan harga diri bangsa.
Seperti kisah bajak laut yang memburu One Piece, 80 tahun kemerdekaan yang kita rayakan ini adalah peta, bukan tujuan. Ia memberi arah, tapi tidak menjanjikan isi.
Ia membuka peluang, tapi tidak menggaransi isi perut rakyat kenyang. Maka harta karun berupa keadilan sosial, pendidikan merata, biaya kesehatan terjangkau, kebebasan berpikir, dan hidup bermartabat, harus dicari dengan keringat setiap orang.
Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa hanya diserahkan pada elite. Tidak cukup hanya diperingati dengan upacara saban Agustus. Harta karun bangsa ini bukanlah hadiah dari sejarah.
Ia adalah hasil dari kerja keras kolektif yang tidak boleh putus. Dan satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan terus mencari secara bersama sekalipun berbeda-beda cara.
Dirgahayu Indonesia ke-80!.**
IJA SUNTANA (Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Sumber : Kompas.Com




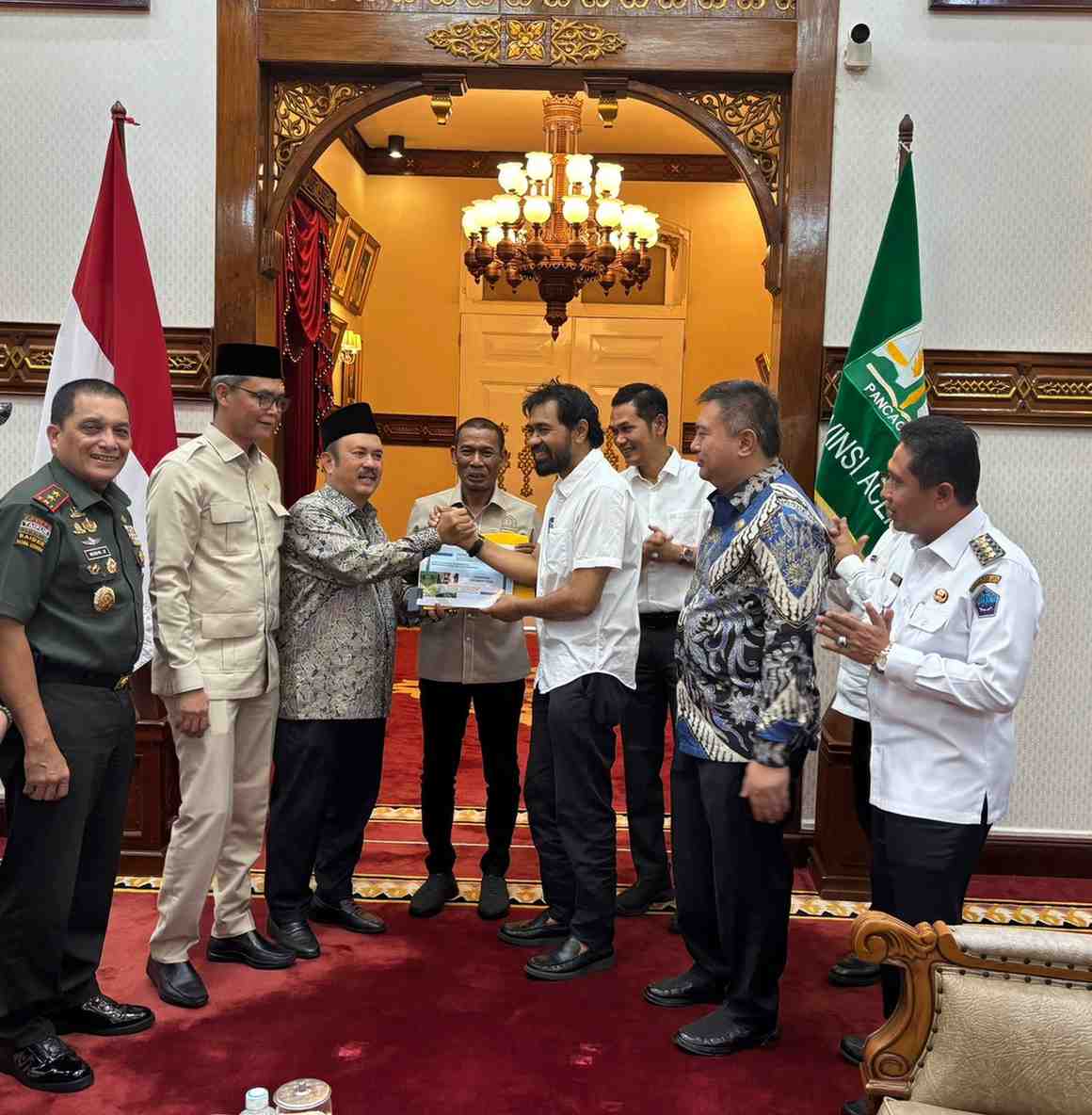









Tidak ada komentar